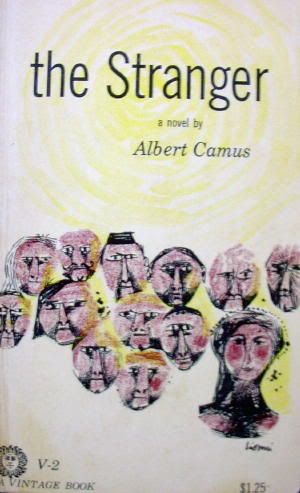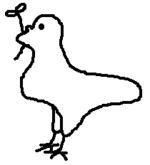"Hai apa kabar? Sudah lama
ga ketemu."
Bangsat! Masa hanya itu yang bisa aku pikirkan. Padahal, tiga bulan gaji yang tak seberapa kuterima telah dihabiskan untuk membeli tiga buah buku; sebuah roman picisan, sebuah buku tips mendapatkan perempuan dalam seminggu, dan buku tata cara menghipnotis pikiran perempuan. Tapi, cuma itu yang bisa aku pikirkan. Sialaaan!
Malam sudah menembus level akhir, tepatnya 23.30 WIB. Jakarta masih saja menari. Deru berbagai kendaraan masih saja mampir di daun telinga yang mulai emoh menyimak kenapa. Terkadang jerit sirine mobil entah polisi atau ambulans atau mungkin mikrolet yang sok menakut-nakuti mobil di depannya, menyelinap di antara gemuruh tak henti. Jika sedang beruntung bisa terdengaran lantunan pria khas Madura meneriakan sebuah kata panjang.
"SATEEEEEEEEEEEEEEEE!"
Kamar kost-an ini memang terletak tepat di pinggir jalan di ujung selatan kota
megapolitan ini. Ruas jalan yang tak terlalu besar kerap kali dilalui truk, bus, dan kendaraan lainnya yang hendak memasuki Jakarta dari pintu selatan. Lazimnya mereka membawa berbagai oleh-oleh dari kota-kota di kaki Gunung Gede-Pangrango dan Halimun. Puluhan keranjang berisi ayam, sayuran, buah, atau buruh yang komuter pada malam hari mengiringi kendaraan berbentuk aneh penyebar aspal
hotmix.
Kamarku hanya dibatasi dinding tipis dengan kamar tetangga yang hingga kini tak kukenali siapa nama-nama mereka. Kusen jendela yang keropos seperti enggan menggenggam kaca yang menempel, hingga tiap mobil besar lewat dia selalu bergetar menimbulkan bunyi seperti kekeh menyebalkan. Dari bawah daun pintu triplek yang
ngatung kerap menyelinap mahluk menjijikkan seperti tikus ataupun coro.
Semua itu menjadi tetangga yang paling sering menyambangi dibanding tetangga lain berwujud orang. Sudah setahun aku tinggal di Jakarta. Kebiasaan para penghuni kota ini tak pernah bisa kumengerti. Mungkin aku sendiri terlalu sibuk, meski untuk mencoba mengerti. Aku tak ada niat mengenal tetangga, aku ingin tak dikenal. Toh mereka sendiri tak ada niat mengenalku. Malas! Jakarta memang aneh.
"Kenali tetangganya dong Mas. Kalau ada apa-apa kan bisa ada yang membantu," kata Sum suatu ketika. Entah kenapa dia bicara begitu, mungkin karena dia melihatku tak pernah punya teman.
Di kota ini sebuah senyuman bisa dianggap sebuah ancaman. Bukannya akan dibalas senyum, salah-salah malah digebuk orang. Mungkin karena tak ada hal yang gratis di ibukota ini. Itu pula yang membuatku selalu langsung masuk kamar sepulang kerja, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Persetan dengan tetangga.
Ah iya, Sum, Sumiati. Perempuan yang membuatku merasa sakit di dalam pinggang. Kadang-kadang merasa sesak di dada. Tapi merasa nyaman saat mendengar suaranya. Dialah alasan utama aku tinggal lama di kota ini. Kota yang setiap hari mempertemukan muka-muka baru di hadapanku. Datang dan pergi, entah kemana. Hanya berpapasan, tanpa ekspresi, melintas tanpa sapa.
Ah, mengapa memikirkan kota dan penduduknya yang aneh ini. Biarkan hanya koran dan para pujangga saja yang memikirkan kota asing ini. Bahkan koran nomor dua yang tergeletak di atas mejaku sudah tersiram kopi hitam yang sedianya menemaniku merangkai jurus menggaet Sumiati. Ya, Sum, perempuan penghuni mesin jahit nomor delapan di pabrik garmen tempatku bekerja. Perempuan yang setiap harinya, selama 16 jam lebih selalu kulihat menempel pada mesin jahit produk Cina.
Selama itu, binar matanya tak pernah lepas mengomandoi jemari lentiknya menari-nari menuntun benang-benang perajut kaos bermerek yang hanya dijual di luar negeri. Aku selalu kagum dengan keperkasaan perempuan itu. Meski setiap bulan hanya menerima gaji yang masih kurang bila ingin membeli sepatu bola merek adidas yang diiklankan David Beckham, toh ia tetap antusias dengan pekerjaannya.
"Aku harus kerja Mas. Buat bantu adikku, si Adi, biar dia bisa sekolah. Sampai dia lulus SMA deh, supaya aku bisa tenang," ujarnya suatu saat ketika aku mampir membeli pisang goreng yang ia jajakan sebelum ia memasuki kerangkengnya untuk bekerja.
Aaah, dialah perempuan idamanku. Seorang perempuan yang kegagahannya melebihi kegagahan seorang aparat yang kerjanya nyegatin sopir mikrolet di persimpangan depan. Ya, kegagahan menghadapi permasalahan hidup, tanpa menjadi masalah bagi hidup orang lain. Dialah jiwa yang aku cari untuk mengisi kerangka yang hilang di pinggangku.
"Dikuliahin malah
drop out! Mau jadi apa kamu? Jadi pegawai pabrik?!"
Itu wejangan terakhir ibuku, saat aku meninggalkan kota kelahiranku lima tahun lalu. Apa salahnya jadi pegawai pabrik. Buktinya, aku menemukan Sum yang jauh lebih mulia dari semua direktur perusahaan multinasional yang fotonya terpampang di setiap sudut ruang rumah orangtuaku di sana. Sum.. Sumiati, perempuan dengan keindahan memancar yang hingga kini tak pernah kuketahui dimana rumahnya.
Keindahan bukan datang dari banyaknya kepala tertunduk karena takut dipecat, berjejer setiap melangkah. Keindahan justru datang dari ketegaran jiwa yang membuat sesuatu di dalam pinggang melilit dan kedua bola mata berkaca-kaca. Keberanian, perjuangan, dan ketabahan. Itulah Sumiati, perempuan yang hilang dari dalam pinggangku.
Aaah, dia terlalu indah untukku. Meski ruang tempat mesin jahit yang sering ia duduki berada dalam kerangkeng kawat yang dikunci
supervisor galak yang badannya semakin bengkak setiap kutemui. Kerangkeng kawat tersebut merupakan ruang koleksinya, tempat ia menyimpan angsa-angsa indah yang bertelur emas. Tapi hanya satu angsa yang hampir meledak meluberi otakku. Dialah Sum.. Sumiati.
Sudah puluhan, bahkan ratusan angsa pergi meningalkan sangkar tersebut akibat kejenuhan, ketidakpuasan, atau kalah. Hanya Sum yang selalu bertahan, menghasilkan jutaan telur emas yang memperkaya para petinggi perusahaan yang menggurita di seluruh dunia. Sum bertahan bukan karena ambisi karir (tak ada karir di dunia sangkar kawatnya), bukan karena putus asa, bukan karena gaji yang jelas-jelas jauh di bawah standar UMR. Dia bertahan karena sebuah harapan, harapan memandang dunia yang layak di depan adik satu-satunya. Dunia yang ia sendiri tak pernah mengecapnya. Itulah Sum, Sumiati-(ku).
Kopi yang tumpah di atas koran nomor dua bergambar orang kontet yang juga nomor dua di negara ini, mulai menetes akibat gravitasi. Bercak hitam jelas tampak di bungkus gorengan yang terbuat dari koran dengan berita lintas dengan judul "Grup Bukaka menguasai proyek-proyek infrastruktur, selebihnya dikuasai Ical". Ah, apa pula pembangunan infrastruktur, toh hasilnya tak pernah nyata dirasakan oleh orang-orang seperti Sum. Nampaknya, berita seperti itupun tidak istimewa, buktinya hanya menghiasi berita lintas di koran yang ga jelas asal muasalnya itu.
"Fokus! Fokus! Bagaimana caranya
dapatin Sum, itu yang utama!"
Semua buku bekas yang aku temukan di emper jalan dan berderet di rak darurat di sudut kamar masih saja bisu. Lembaran kertas kusut semakin menumpik di atas kasur butut, tak ada rumusan kata yang cukup indah bagi jiwa seperti Sum. Dua tahun menggeluti pelajaran sastra di kota gudeg sepertinya tak cukup. Bahkan sastra sendiri akan malu, mengkerut dihadapan Sum. Lalu apa dayaku mendapatkan Sum.. Sumiati.
Radio transistor masih mendendangkan Meggy Z, suaranya tergagap-gagap, entah chanelnya tak tepat atau baterenya sudah sekarat. Baiklah, sastra bukan cara yang tepat, dangdut mungkin akan lebih cepat.
Bullshit dengan sastra, yang penting isi kepalaku harus mengalir, biar isi pinggang tak lagi melilit. Biarlah gagal menjegal, yang penting aku tak akan menyesal meski memiliki Sum akan batal.
Segelas kopi lagi mungkin akan memperlancar makna yang ingin kusampaikan, mengalir melalui tinta penaku. Yaa, hanya segelas kopi hitam dengan sebatang rokok, teman setiaku dalam setiap keadaan. Mereka sahabat yang memberikan jalan bagi isi kepalaku agar menjadi makna.
"Segelas kopi hitam sudah tersedia, sebatang rokok telah menyala. Tunggu aku Sum!"
Hai Sum, masih ingat aku ndak? Aku pembeli setia pisang goreng yang hingga kini masih mengutang untuk lima biji pisang goreng buatanmu. Sebenarnya aku mau ngomong langsung, tapi aku ndak berani..."PAK RT! PAK RT! BANGUN PAK!"
Jeritan suara sopran mencegat perjalanan khayalku yang coba mengalir ke dalam lembaran kertas. Suara tersebut jelas terdengar dari kamar tetengga yang merupakan ketua RT di lingkungan ini. Ia lah pemilik petakan kamar yang menurut dia sendiri, seluruhnya dihuni pegawai pabrik termasuk diriku sendiri.
"Iya..iya..!" Suara lemah terdengar menjawab. Nampaknya, pak RT telah terlelap sebelum gedoran di pintunya membangunkan. Bunyi putaran kunci terdengar diikuti
kreot pintu triplek yang sepertinya telah dibuka pak RT.
"ANU PAK.. SI ADI..."
"Ada apa dengan si Adi Bu?"
"Si Adi nangis di depan kamarnya Pak!"
"Lho Ibu ini, ya ga apa-apa toh kalo dia nangis. Laki-laki juga kadang bisa nagis loh Bu. Paling-paling dia diputusin pacarnya."
"Bukan Pak! Anu Pak, waktu saya tanya kenapa, dia bilang kakaknya mati. Itu loh Pak si Sum, Sumiati!"
"Yang benar toh Bu! Ibu sudah melihatnya? Kemarin emang dia ngaku agak demam, tapi masa bisa meninggal?"
"Iya Pak RT, saya sama suami saya sudah melihatnya. Dari hidung, telinga, dan mulutnya keluar darah! Dan..dan.. yang jelas dia ga bernafas! Sudahlah Pak ayo lihat sendiri, saya ga tega melihatnya, juga melihat si Adi. Dia lagi ditemani suami saya, ayo Pak!"
"Iya iya. Ayo kita ke sana Bu!"
Keributan sejenak tersebut berlalu begitu saja, hanya bara dari rokokku yang membangunkan kesadaran. Kopi dalam gelas kedua telah tumpah tanpa disadari. Air hitam menggenangi lembaran kertas yang sedianya menjadi surat buat Sum, Sumiati si pejuang gagah, Sumiati-(ku).
Ruang redaksi koran nomor dua
abdisalira©171005